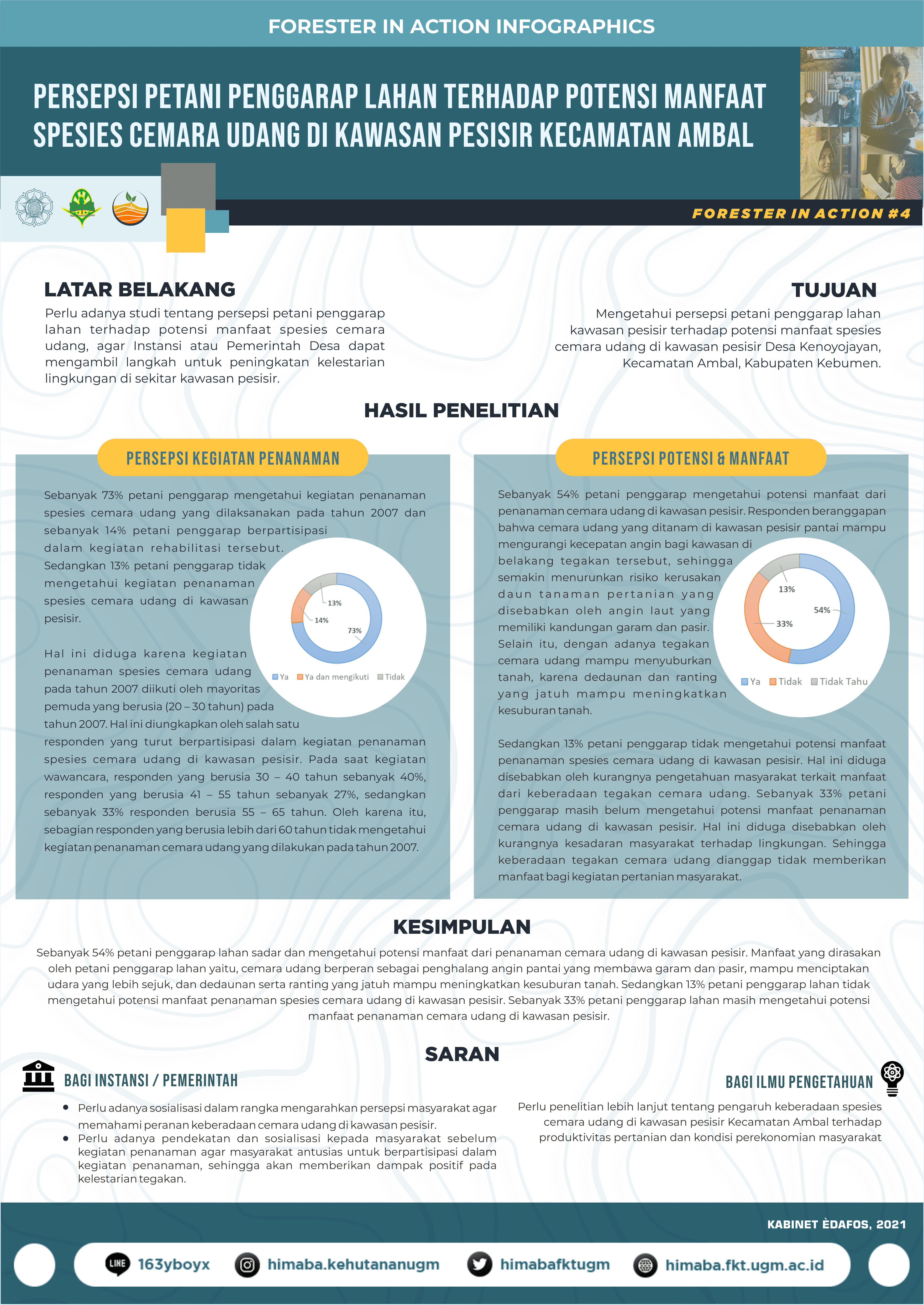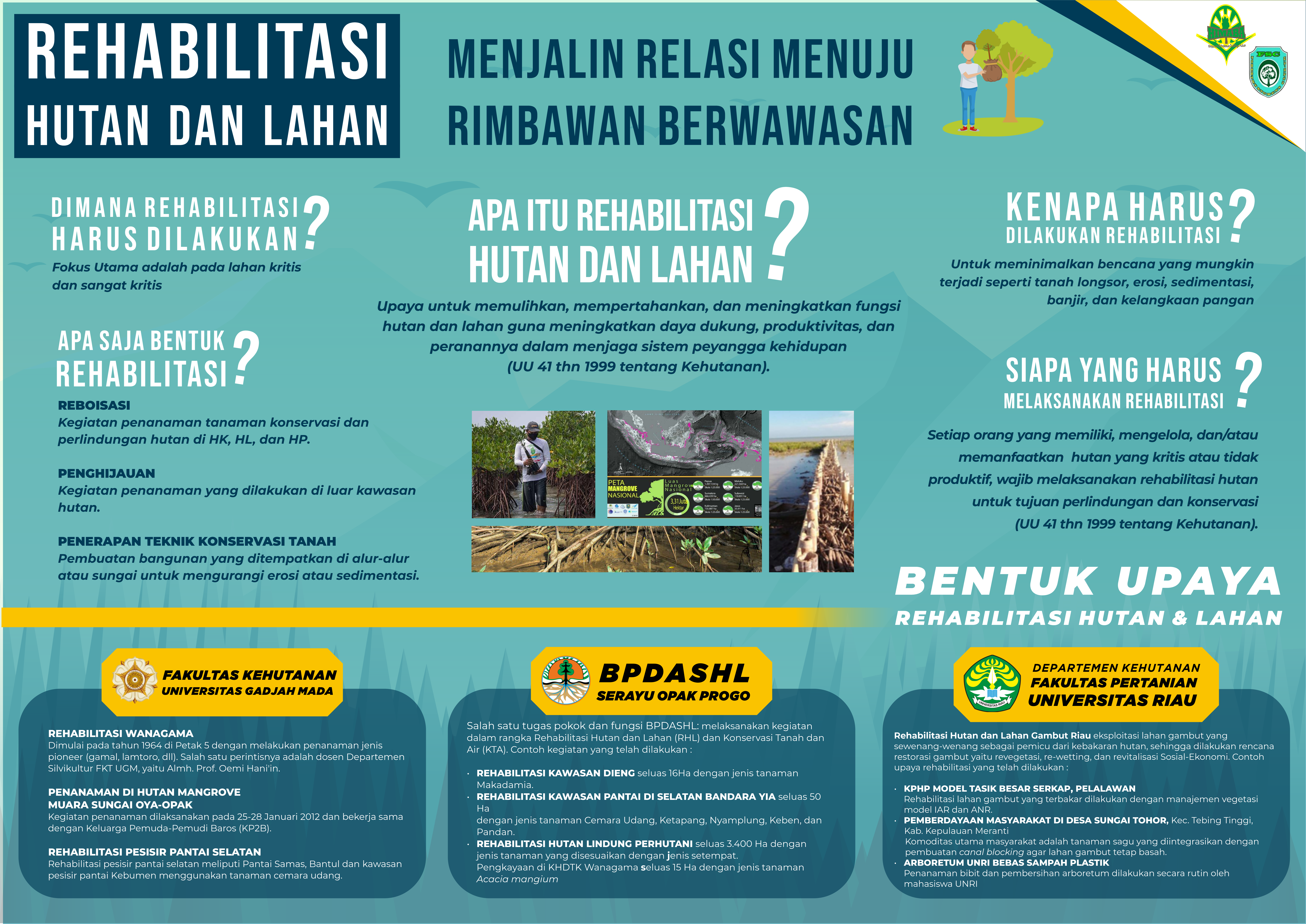Sumber gambar: Canva.com
Konservasi Biodiversitas Pandan Laut dan Penyu sebagai Bentuk Pelestarian Ekosistem Ekoton Pantai yang Berkelanjutan
Ekosistem didefinisikan sebagai interaksi antara komponen yang satu dengan yang lain. Untuk memahami interaksi antara komponen yang satu dengan yang lain, maka perlu memperhatikan bagaimana tumbuhan (komponen biotik) memerlukan komponen abiotik, seperti tanah, air, atau cahaya untuk tumbuh. Perhatikan bagaimana hewan pemakan tumbuhan tersebut menjadi sumber makanan hewan pemakan daging, hewan atau tumbuhan yang telah mati juga mengalami penguraian oleh komponen-komponen biotik yang kemudian bermanfaat bagi tanah. Tanah tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan tumbuhan hingga menghasilkan sumber pangan manusia dan hewan. Ekosistem memiliki ciri khas ketergantungan terhadap dua komponen atau lebih, seperti penjelasan diatas yakni ketergantungan komponen biotik dengan abiotik serta biotik antar biotik dengan rantai makanannya (Latumahina, F., Mardiatmoko, G., dan Sahusilawane, J., 2019). Ekosistem diklasifikasikan berdasarkan tempat pembentuk (ekosistem perairan pantai, air tawar, hutan tropis, dan lain-lain). Berdasarkan proses, terdapat ekosistem alami tanpa bantuan manusia dan ekosistem buatan seperti lingkungan konservasi. read more