
Sumber: Canva.com
Penopang Kehidupan : Biodiversitas Hutan
Biodiversity atau keanekaragaman pada hutan tidak melulu berbicara mengenai makhluk hidup. Lebih dari itu, ada beragam aspek penting yang menjadi penyokong kehidupan di hutan. Potret nyata hutan menjadi sangat miris karena angka biodiversitas hutan yang ada semakin menurun. Di dalam hutan terdapat milyaran kehidupan organisme yang bahkan menghidupi kehidupan lainnya. Hal lain yang menjadi penting adalah bahwa hutan merupakan “pabrik” dari beragam kekayaan alam. Ketidakmengertian, ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap pentingnya hutan banyak menyebabkan minimnya pengetahuan dalam mengelola hutan. Padahal, hutan diibaratkan sebagai penopang kehidupan selaras dengan pernyataan dan ajakan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Hari Hutan Internasional (HHI) yang menyatakan bahwa hutan Indonesia memiliki peran strategis sebagai sistem penopang kehidupan (Life Support System). Hutan hujan Indonesia, menjadi rumah bagi ribuan jenis spesies yang beragam. Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan hutan di Indonesia yaitu 125.797.052 ha yang terbagi menjadi beberapa bagian. Indonesia memang patut bangga atas julukan negara megabiodiversity. Daratan Indonesia hanya mencakup 1,3% daratan bumi, tetapi Indonesia memiliki 10 % tumbuhan, 12 % mamalia, 16% reptil dan amfibi, serta 17 % burung yang ada di dunia (Collin et al. 1991). Merilis data dari BAPPENAS, Indonesia setidaknya memiliki lebih dari 38.000 spesies tumbuhan, 55% diantaranya adalah tumbuhan endemik.





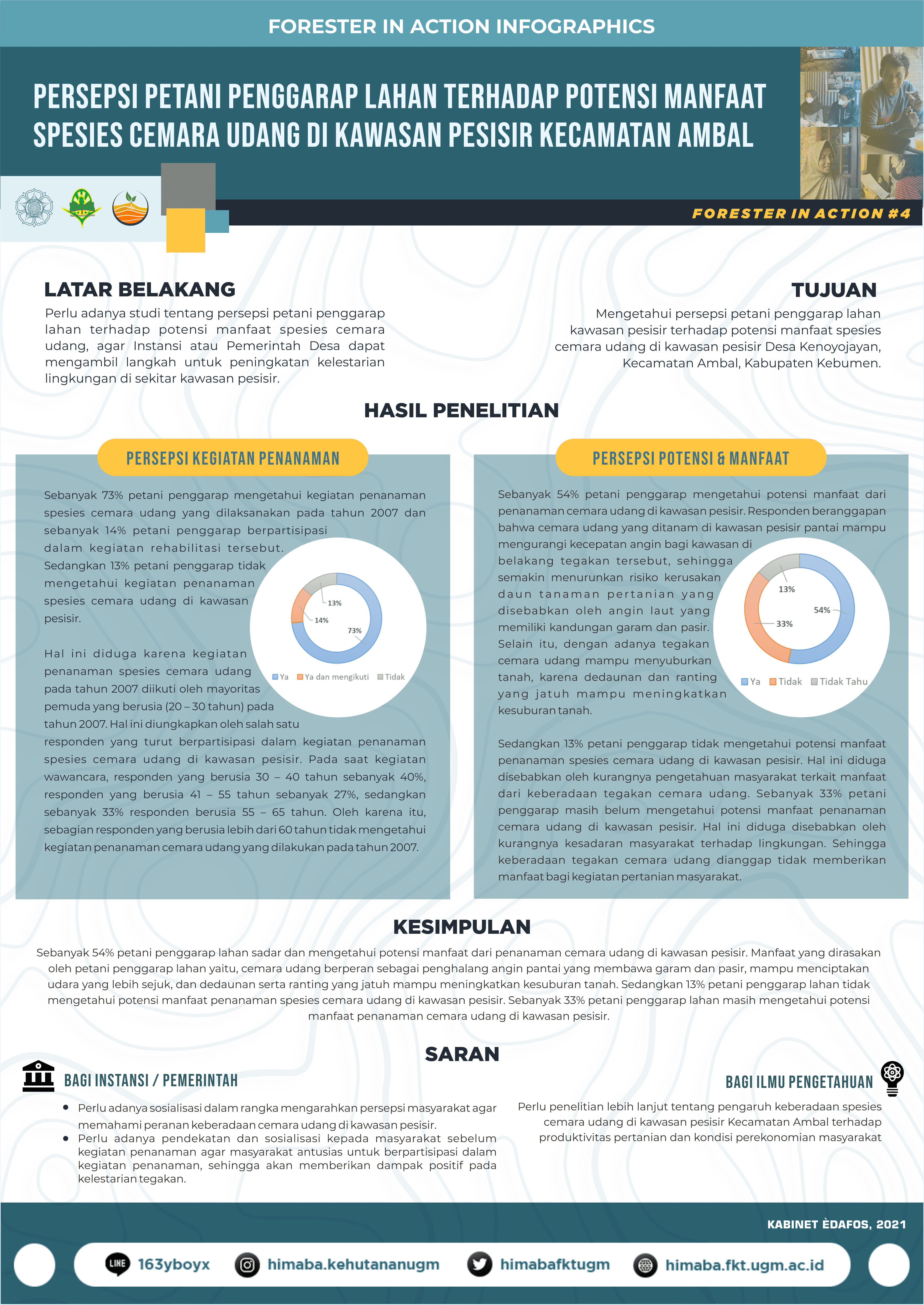





 picture source : new.mongabay.com
picture source : new.mongabay.com