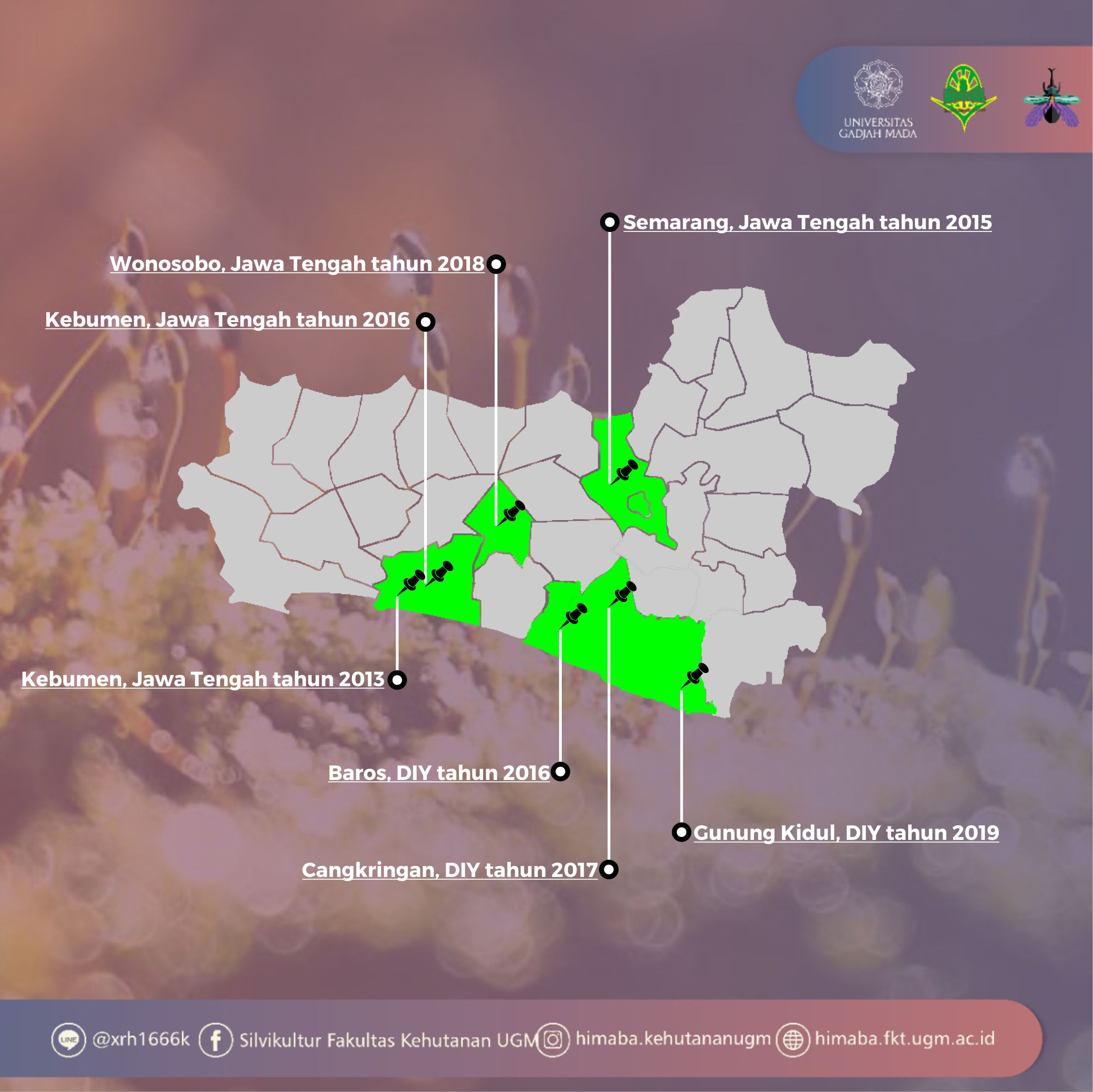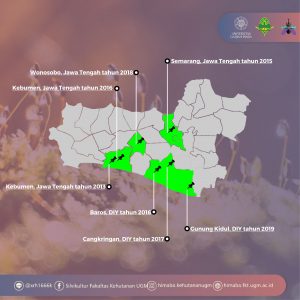pict : Rahmanto, 2020
Pada tahun 2020, Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas 3.311.207,45 ha yang terbagi menjadi kawasan hutan dan luar kawasan (Rahmanto, 2020). Hutan mangrove di Indonesia banyak ditemukan di berbagai wilayah terutama di Papua, Kalimantan, dan Sumatera (FAO, 2007). Sekitar 3 juta ha hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Jumlah ini mewakili 23% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia (Giri dkk., 2011).
Hutan mangrove tumbuh di antara garis pasang surut, pantai karang, daratan koral mati yang di atasnya ditimbuni pasir atau lumpur, dan pantai berlumpur (Saparinto, 2007 dalam Rahim dan Banderan, 2007). Hutan mangrove memiliki karakteristik tanah yang berlumpur dan hutannya selalu digenangi air (Fatma, 2016). Komunitas vegetasi hutan mangrove pantai tropis didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Rahmanto, 2002). Selain itu, komposisi vegetasi yang menyusun ekosistem mangrove relatif homogen dikarenakan hanya vegetasi tertentu yang bisa hidup di masing-masing zonasi yang ada. Pembagian zonasi pada ekosistem mangrove dibagi menjadi empat, yaitu zona mangrove terbuka, zona mangrove tengah, zona mangrove payau, dan zona mangrove daratan. Zona mangrove terbuka merupakan zona yang berhadapan dengan laut dan didominasi oleh Sonneratia alba. Zona mangrove tengah terletak di belakang mangrove zona terbuka dan di dominasi oleh jenis Bruguiera sp. dan Rhizophora. Zona mangrove payau berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar dan didominasi oleh komunitas Nypa atau Sonneratia. Sedangkan zona mangrove daratan berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya dan didominasi oleh jenis Ficus microcarpus, Intsia bijuga, Nypa fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus sp., dan Xylocarpus moluccenis. Zona ini memiliki kekayaan jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan zona lainnya (Noor dkk., 2006). read more